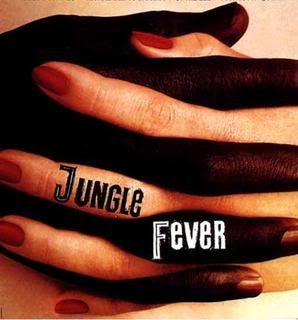Rojali dan Juleha, Galih dan Ratna, atau Romeo and Juliet dalam skala internasionalnya, bisa dikatakan sebagai kisah kasih yang tak hanya terjadi di SMA. Kisah mereka bertahan sepanjang masa. Namun bagaimana dengan Rama dan Shinta/Sita? Apakah bisa dikatakan pula bahwa kedua sejoli ini memiliki kisah cinta sejati yang bikin iri semua pasangan suami-istri? Dimana Sita--sang istri--terkenal setia dan Rama--sang suami--sungguh gagah perkasa. Sampai-sampai banyak film India yang menggunakan nama Rama dan Sita sebagai nama karakter yang diceritakan saling mencinta.
Rojali dan Juleha, Galih dan Ratna, atau Romeo and Juliet dalam skala internasionalnya, bisa dikatakan sebagai kisah kasih yang tak hanya terjadi di SMA. Kisah mereka bertahan sepanjang masa. Namun bagaimana dengan Rama dan Shinta/Sita? Apakah bisa dikatakan pula bahwa kedua sejoli ini memiliki kisah cinta sejati yang bikin iri semua pasangan suami-istri? Dimana Sita--sang istri--terkenal setia dan Rama--sang suami--sungguh gagah perkasa. Sampai-sampai banyak film India yang menggunakan nama Rama dan Sita sebagai nama karakter yang diceritakan saling mencinta.Tampaknya hal ini tak berlaku bagi Nina Paley, perempuan nyantey, walaupun pernah patah hatey, yang saya yakin tak suka makan petey. Alih-alih memercayai jargon “kisah cinta terbaik sepanjang masa” untuk cerita Rama dan Sita, ia lebih suka dengan “kisah putus terburuk sepanjang masa”.
Sarkas? Tidak juga. Mari kita selami isi kepala sang sutradara! Akan lebih baik apabila kita memposisikan diri sebagai wanita.
Nina Paley yang patah hati karena ditinggalkan sang (mantan) kekasih menyadari bahwa kisah hidupnya sebelas-duabelas dengan kisah hidup Sita, simbol perempuan suci sekaligus istri berbakti. Sita begitu memuja suaminya, Rama – kesatria yang gagah perkasa sekaligus titisan dewa yang dipuja-puja, yang ironisnya, tak pernah dikenal sebagai suami yang (bahkan mendekati) sempurna. Bukan tak mungkin apabila Rama tak mendapat julukan sebagai suami yang baik karena tak ada catatan sejarah yang menyebutkan tentang itu (nah yang ini mohon dicek kebenarannya). Sebaliknya, justru ia melakukan hal yang paling membuat para istri tersiksa (selain selingkuh, tidak memberi nafkah, tukang mabuk dan judi, poligami, dan KDRT) yaitu menaruh ketidakpercayaan setingkat dengan harga dirinya... tinggiiii sekali.

Sita yang begitu terhormat dan setia pada Rama, bahkan sampai mendapatkan sertifikasi halal dari para dewa, justru tak dipercayai oleh suaminya sendiri yang lebih mementingkan harga diri sebagai pria yang notabenenya lebih tinggi dari wanita. Rupanya diam-diam Rama senang bernyanyi. Dan sebuah lagu yang sangat digemarinya adalah sebuah lagu yang berbunyi ‘wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu’. Namun kepiawaian Rama dalam bernyanyi tak ditunjukkan di sini, karena Sita lah yang memegang peranan dalam menyuarakan isi hati dalam bentuk lagu-lagu syahdu bernuansa biru, yang kita kenal sebagai blues.
Kisah yang seharusnya sedih bila dilihat dari kacamata perempuan justru dibalut dengan suasana ceria di film ini. Hal ini bisa jadi disebabkan karena gambar karakter yang menyenangkan untuk disaksikan dan lagu-lagu yang menenangkan untuk disenandungkan. Sehingga sang creator film ini merasa tak perlu lah lebay sampai menangis bombay demi sebuah cerita sedih.
***
Wayang 1 : “Kalau tak salah, kita mulai jam 4...”
Wayang 2 : ”Jam setengah 5!"
Wayang 3 : “Euuhh... lebih tepatnya jam setengah 5-an!”
Wayang 2 : “Yaah... sebelas dua belas!”
Wayang 1 : “Ngomong-ngomong, siapa saja yang datang ya?”
Wayang 2 : “Andika pasti...”
Wayang 1: “Ya, tentu! Sang fasilitator! Dan sang pembawa film, sekaligus the feminist one, Regie! Oh maaf memotong, silahkan!”
Wayang 2 : “Euuuh... yang perempuan kacamata itu... Maknyus, Maknyos, Nyesmak,...”
Wayang 3 : “Maknyes!”
Wayang 2 : “Oh ya! Nama macam apa itu?! Dia juga membawa temannya, Dita, yang tertidur di salah satu bagian film.”
Wayang 3 : “Ck ck... Kok bisa-bisanya?! Lalu ada Resti.”
Wayang 1 : “Ya... dia datang telat. Daaan... perempuan memakai baju pesta!”
Wayang 2 : “Lia! Haha... dia mau kondangan ternyata!”
Wayang 3 : “Lalu laki-lakinya ada Aji...”
Wayang 1 : “Yang sudah agak gondrong!”
Wayang 3 : “Dan si laki-laki berwajah lucu itu...?!”
Wayang 1 : “Rizal!”
Wayang 3 : “Oh ya! Dan Niken si sarjana psikologi!”
Wayang 2 : “Yang sekaligus berjualan celana dalam!”
Wayang 1, 2, 3 : (Tertawa)
Wayang 2 : “Dan ada dua sejoli yang adem ayem duduk di bagian belakang, Faisal dan Uli!”
Wayang 1 : “Oh well, mereka pasangan!”
Wayang 2 : “Oh pantas mesra!”
Wayang 1 : “Kalau tak salah, ada Theo juga?!”
Wayang 2 dan 3 : “Itu di film!”
Wayang 1 : “Oh maaf, saya suka lupa mana film yang saya tonton, mana kenyataan yang saya alami.”
Wayang 2 : “Kalau tak salah karakter itu namanya Laksmini!”
Wayang 3 : “Come on! Itu mah di Tutur Tinular... musuhnya Mantili! She was Lasmini!!”
Wayang 1 : “Wow, jadi kepikiran! Kalau Nina Baley...”
Wayang 2 dan 3 : “Paley!”
Wayang 1 : “Ya, dia... kalau dia membuat Rama dan Sinta dari sudut pandang perempuan, mungkin ada sutradara perempuan kita, yang bisa membuat versi Catatan Si Boy, namun dari sudut pandang perempuan-perempuan yang dipacarinya."
Wayang 2 : “Lumayan juga idenya.”
Wayang 1 : “Yaa... kita kan punya banyak sutradara perempuan. Seperti Riri Riza, misalnya?”
Wayang 2 dan 3 : “Riri Riza tuh laki-laki!”
Wayang 1 : *benjol
 Thya (beberapa memanggilnya Maknyes) adalah insinyur yang sudah sama sekali lupa mengenai ilmu tentang keinsinyurannya dan berjanji tak akan kembali ke bidang itu. Profesinya saat ini adalah penyiar di sebuah radio anak muda di Bandung. Hobi menulisnya dituangkan ke http://rahmathya.multiply.com/ dan khusus untuk cerpen-cerpennya ia tuangkan di http://ceriterathya.blogspot.com/
Thya (beberapa memanggilnya Maknyes) adalah insinyur yang sudah sama sekali lupa mengenai ilmu tentang keinsinyurannya dan berjanji tak akan kembali ke bidang itu. Profesinya saat ini adalah penyiar di sebuah radio anak muda di Bandung. Hobi menulisnya dituangkan ke http://rahmathya.multiply.com/ dan khusus untuk cerpen-cerpennya ia tuangkan di http://ceriterathya.blogspot.com/